(Penulis Drs.Ec. Agung Budi Rustanto – Pimpinan redaksi Tabloid Infoku
Diolah dari 6 Sumber Berbeda)
POLITIK uang
bukanlah suatu hal yang baru di pentas politik Indonesia. Jauh sebelum keriuhan
soal merebaknya politik uang di ajang pilkada maupun pileg dan pilpres, yang
diartikan sebagai praktik bagi-bagi uang kepada massa pemilih untuk memperoleh
dukungan suara.
Sebenarnya politik uang telah terjadi lama sejak sistem pemilihan
sebelumnya yang menganut sistem tidak langsung atau keterwakilan melalui
DPR/DPRD.
Hal yang membedakan adalah pada sistem sebelumnya politik uang berlangsung
dalam sirkuit yang terbatas dan tertutup yang dipusatkan pada lobi-lobi di
jaringan partai politik, sementara pada sistem pemilihan langsung, politik uang
terkait dengan transaksi langsung antara para calon dengan massa pemilih.
Pada sistem pemilihan langsung, para calon yang bersaing tidak lagi bisa
bergantung sepenuhnya pada mesin-mesin partai politik di dalam memenangkan
persaingan. Realita bahwa basis suara partai seringkali tidak identik dengan
basis suara sang calon membuat dukungan partai politik tidak serta-merta
menjamin kemenangan dia, sehingga para calon harus kreatif dan mandiri di dalam
membangun basis-basis suara.
Umumnya mereka hanya menggunakan partai politik sebagai kendaraan politik untuk mendaftar mengikuti proses pemilihan, dan kemudian mengandalkan tim sukses masing-masing untuk memastikan kemenangan.
Berhadapan langsung dengan massa pemilih bukanlah suatu hal yang mudah.
Kemampuan menarik dukungan tidak hanya terbatas pada kriteria-kriteria
normatif, seperti kompetensi, visi-misi dan karya.
Membangun popularitas di kalangan pemilih juga membutuhkan kemampuan
menawarkan dan memberikan imbalan atas dukungan politik.
Populeritas atau kinerja yang baik dari calon seolah, menjadi penilaian
nomor urut yang ke 16, dikalahkan dengan besaran pemberian uang menjelang
pilkada.
Karena bagi massa pemilih, pelaksanaan pilkada tidak lagi dilihat sekedar
sebagai sebuah pesta demokrasi, melainkan juga sebagai ajang transaksional
untuk memperoleh keuntungan pribadi pada saat proses pilkada maupun pasca
seorang calon terpilih.
Terjadi peningkatan kesadaran pada masyarakat bahwa hak suara mereka bisa
dijadikan komoditas yang dipertukarkan dengan uang dan jenis kompensasi
lainnya, tidak hanya sekedar dipertukarkan dengan tuntutan perbaikan
kesejahteraan yang abstrak.
Ironisnya hal ini terjadi di saat juga terdapat kesadaran tentang retorika
tata pemerintahan yang baik dan bersih, yang mencakup pemerintahan yang bebas
korupsi, akan tetapi massa pemilik tetap tidak canggung untuk mengharapkan
imbal balik dari para calon.
Penyebab dari kesemua ini bersumber pada pesimisme masyarakat bahwa calon
yang bertarung di pilkada memiliki komitmen yang serius untuk mewujudkan tata
pemerintahan yang baik dan bersih. Hal ini kemudian membuat masyarakat merasa
tidak masalah maupun bersalah jika sejak dari awal juga mengambil untung dari
para calon.
Selain itu ternyata politik uang juga merupakan salah satu cara bagi para
calon untuk membangun kharisma dan meyakinkan masyarakat pemilih tentang
kemampuan mereka untuk memenuhi tuntutan para pemilih mereka jika kelak
terpilih.
Oleh masyarakat, ‘tingkat keroyalan’ para calon selama proses pilkada
dijadikan tolak ukur atas kemampuan mereka untuk meredistribusikan keuntungan
yang akan mereka peroleh jika menjabat kepada masyarakat pemilihnya.
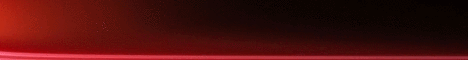
Sikap pragmatis masyarakat terhadap politik uang menjadi cerminan
bahwa masyarakat Indonesia masih belajar untuk berdemokrasi.
Akan tetapi dengan semakin diterimanya politik uang, tantangan untuk
mewujudkan demokrasi yang ideal di Indonesia menjadi semakin rumit.
Kesadaran bahwa kompetensi, visi-misi dan karya saja bukanlah jaminan
memadai untuk memenangkan pilkada karena kuatnya pragmatisme massa pemilih
terhadap politik uang, membuat semua calon menjadi terbuka untuk melakukan
praktik kotor ini yang dilakukan secara terbuka maupun tersamar.
Saat ini politik uang telah menjadi penyebab utama membengkaknya biaya
kampanye yang harus ditanggung oleh para calon.
Pembengkakan tersebut kemudian memperbesar risiko penyalahgunaan kekuasaan
jika calon tersebut terpilih untuk memperoleh kembali biaya kampanye yang telah
dikeluarkan.
Kitika hal itu terjadi, kemudian menjadi anti-klimaks maupun ironi dari harapan
besar masyarakat untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih.
Hal ini karena kegagalan mewujudkan harapan tersebut tidak lepas dari sikap
pragmatis dan permisif mereka sendiri terhadap politik uang.
Adakah pilkada yang bebas politik uang, masyarakat Blora-lah
sendiri yang menilainya.###








0 Comments
Post a Comment