(Penulis Drs Ec Agung Budi
Rustanto – Pimpinan Redaksi tabloid INFOKU – diolah dari 7 sumber berbeda)
Tidak lama lagi, perhelatan demokrasi elektoral akan
dilaksanakan. Kita bersyukur karena beberapa calon pemimpin sudah ditentukan
dan kini sedang "mendekatkan" diri kepada masyarakat.
Konsolidasi politik seperti itu
adalah keniscayaan dalam demokrasi elektoral, sebab hanya dengan begitulah
publik bisa menilai siapa calon yang layak untuk diberi kepercayaan.
Rakyat memang pantas untuk mendapatkan informasi yang komprehensif tentang calon pemimpin agar tidak salah dalam memberikan pilihan politik.
Tentu saja kita berharap agar para
calon pemimpin menyadari bahwa mereka juga adalah "elite-elite
sosial" yang mesti memberikan edukasi politik yang benar kepada rakyat.
Mereka harus mampu menampilkan
diri sebagai tokoh yang memastikan bahwa momentum elektoral tidak menciptakan
situasi distortif. Mereka harus menjadi agen yang mengindari bahaya polarisasi
dalam masyarakat lantas menyebabkan sendi-sendi sosial terfragmentasi secara
masif-destruktif.
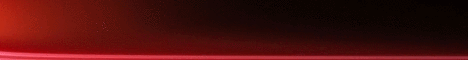
Namun demikian, agaknya harapan
seperti ini tidak mudah terwujud. Kalau kita perhatikan, cikal bakal distorsi
dan polarisasi sudah mulai bermunculan. Ruang publik kita telah menjadi forum untuk
menyebarkan politik kebencian.
Saling hujat kini mulai bertumbuh
ibarat rumput di musim hujan. Kalau tidak diantisipasi secara baik, maka hal
semacam ini akan memproduksi cara berpolitik yang nirdemokratis. Alih-alih
menjadi momentum elektoral bermartabat, Pilkada kita bisa mengandung embrio
perpecahan diantara masyarakat.
Broker/Makelar
Kebencian
Harus diakui bahwa salah satu
metode berkampanye yang akhir-akhir ni cukup tren (mungkin juga dipandang
efektif) adalah viralisasi kebencian melalui ruang publik (seperti media
sosial).
Kebencian didesain secara
pragmatik, lantas menggunakan isu-isu sensitif sambil secara elegan
mengaduk-aduk emosi publik.
Kekurangan calon pemimpin
dieksploitasi lalu direproduksi untuk menjadi rujukan diskursus sosial yang
tentu saja tidak sehat. Publik pun terkooptase lantas mengira bahwa isu valid.
Padahal, yang menjadi orientasi dalam desain pragmatik seperti itu bukanlah
soal benar atau salah, tetapi soal bagaimana tujuan mereka tercapai.
Kita memang tidak bisa memastikan
siapakah dalang yang menciptakan cikal-bakal munculnya potensi keretakan dalam
ruang demokrasi.
Namun demikian, saya meyakini
bahwa ada orang atau kelompok tertentu yang memang bertugas atau juga
ditugaskan secara khusus untuk menciptakan kebencian dan memperkeruhnya menjadi
gerakan yang "mempersekusi" calon atau lawan politik tertentu.
Merekalah yang oleh Cherian George
(2016) disebut sebagai makelar yang berusaha meracik cara/motede lalu
memutuskan apakah menjadi kepentingan mereka untuk memodifikasi provokasi menjadi
gerakan publik.
Mereka memang tidak tampak secara
fisik, tetapi efek destruktif dari apa yang mereka lakukan itu mampu
menghancurkan tatanan sosial politik. Para makelar itu berusaha untuk menjebak
publik agar antipati kepada calon tertentu.
Mereka berusaha
menginsistrumentalisasi khalayak agar mengahakmi seseorang melampaui prosedur
hukum atuapun etika publik tertentu.
Senjata mereka -sekali lagi
-adalah isu-isu sensitif lantas diracik dengan tesis-tesis demokrasi untuk
kemudian memberikan kesimpulan sepihak bahwa tokoh yang mereka lawan itu layak
dibenci, tidak boleh diberi kekuasaan.
Problemnya adalah isu yang mereka
jadikan sebagai rujukan untuk menghakimi calon tertentu itu belum tentu benar.
Kendatipun benar, cara barbarian ala Machiavelli seperti itu tidak dapat
dibenarkan apalagi jika menjadi habitus dalam praksis perpolitikan kita.
Selain itu, tindakan mereka tentu
saja membawa efek negatif bagi calon yang mereka serang dan juga bagi rakyat.
Dikatakan demikian, karena calon itu dicitrakan sebagai seseorang yang tidak
layak mendapat kekuasaan.
Dia "dipersekusi" dan
dikeroyok secara masif lagi liar melalu media sosial. Dia dipersepsikan
sedemikian negatif. Sementara itu, bagi calon bersangkutan, hal seperti ini
juga jelas-jelas merugikan masyarakat sebagai pemilih.
Mengapa? Karena rakyat diperangkap
dalam cara berpolitik "barbarian" yang mendiskreditkan seseorang
tanpa acuan akal sehat.
Rakyat tidak diberi edukasi untuk
memahami bahwa politik adalah matra suci, tetapi malah diajarkan untuk menjadikan
politik itu setali tiga uang dengan kebencian.
Rakyat tidak diajarkan untuk
menjadi pelaku aktif, otonom dan rasional dalam berpolitik, tetapi dikanalisasi
agar memback-up hasrat politik destruktif.
Momentum elektoral yang diharapkan
menjadi saat paling efektif untuk menciptakan proses elektoral demokratis yang
sehat dan ugahari pun menjadi cita-cita yang sulit direalisasikan.
Rakyat yang sebenarnya menjadi
aktor utama dalam berpolitik berubah menjadi hakim publik yang menilai,
mendiskreditkan seseorang melampaui apa yang sebenarnya terjadi.
Momentum elektoral memang
seringkali menjadi pengadilan politik bagi calon pemimpin yang tidak layak
untuk diberi kekuasaan. Tetapi itu bukan berarti pengadilan publik kepadanya
merujuk kepada hasrat-hasrat parsial dari sekelompok orang.
Selayaknyalah rakyat diberi ruang
untuk mengelaborasi rekam jejak, kelebihan dan kekurangan, kapabilitas setiap
calon untuk kemudian secara independen memutuskan untuk memberikan pilihan
politik.
Bahwa dalam berpolitik, saling sikut
itu lumrah. Namun demikian, "legalisasi" politik kebencian melalui
ruang publik adalah sebuah penyangkalan terhadap esensi politik itu sendiri.
Sebab politik tidak pernah dan
tidak boleh memproduksi kebencian, melainkan selalu berpilin erat dengan kebaikan,
solidaritas, pluralisme dan cinta kasih. Kalau pun "saling mencela",
maka basisnya adalah program dan bukannya serangan ad hominem. Program dan
visi-misilah yang mesti dijual kepada publik.
Saya masih meyakini bahwa momentul
elektoral merupakan saat yang paling efektif untuk memeberikan pencerdasan
politik kepada rakyat. Jadi bukan hanya menjadi momentum untuk mendapatkan
kekuasaan.
Karena itulah, elite politik mesti
meracik cara dengan mengintegrasikan cara berkampanye yang berusaha untuk
meredam munculnya kebencian melalui ruang publik.
Elite politik tidak boleh hanya
secara seremonial mengkampanyekan cara berpolitik etis dan edukatif, tetapi
mesti menjadi gerakan kolektif yang mengakar.
Mereka harus mendesain cara
berkampanye agar pentas elektoral tidak menjadi ajang caci maki dan menjadikan
kebencian sebagai rujukan elektoral.
Adalah lebih baik jika kelompok
yang bekepentingan dalam pentas elektoral bahu membahu berusaha melahirkan
peradaban politik bermartabat. Mereka tidak boleh menjadi makelar kebencian
yang berusaha untuk memproduksi dan mereproduksi isu-isu nir-esensial demi
afiliasi dengan calon tertentu.
Kita sudah lelah dengan
ketidakadilan sosial dan seyogianyalah pentas elektoral menjadi momentum tepat
untuk mencari cara memberantas ketidakdilan itu. Amat disayangkan jika pentas
politik elektoral menggiring rakyat untuk terlibat diskursus yang justru tidak
mencerminkan karakter perpolitikan kita.###








0 Comments
Post a Comment